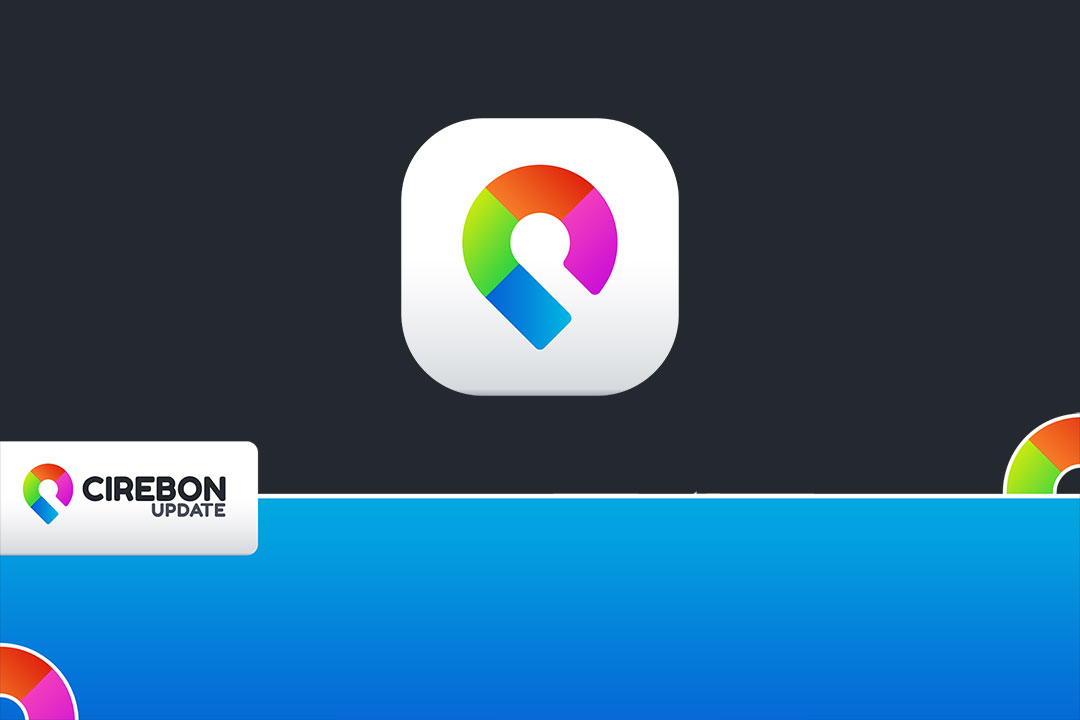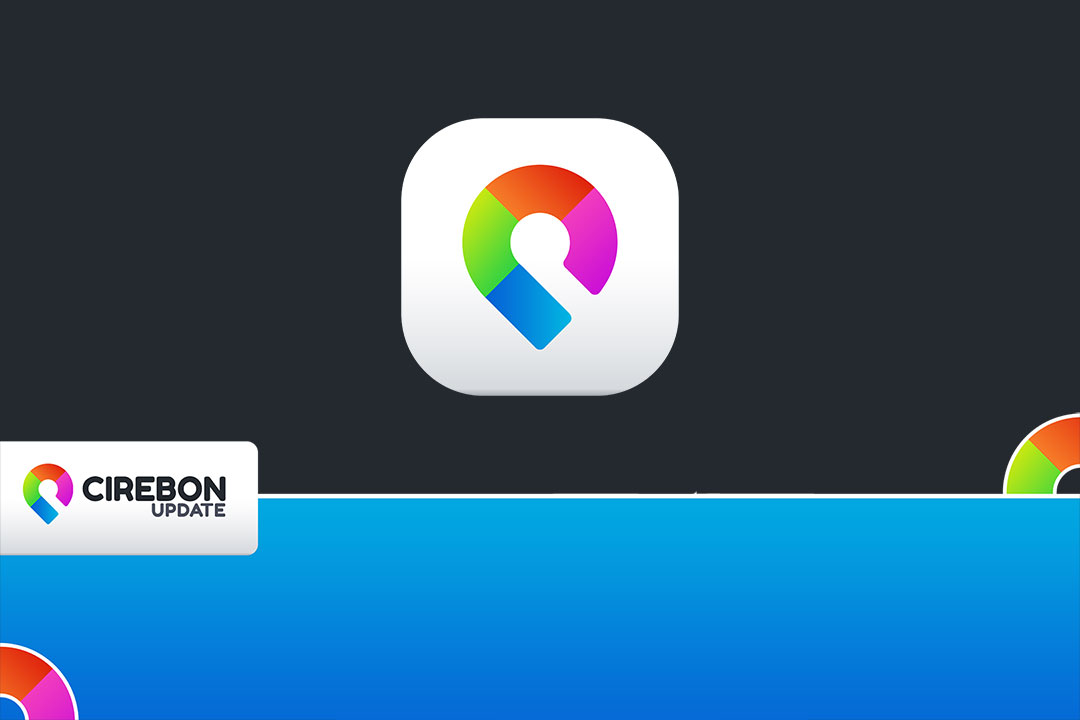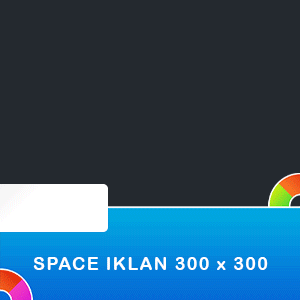Hari itu terasa tenang, keheningannya begitu nyaring. Dua puluh satu tahun telah berlalu dan Galih masih tidak mengerti banyak hal, terutama tentang kedua orang tuanya. Dia seakan merindukan sesuatu yang tidak pernah nyata, hanya sebuah ilusi. Semua upaya untuk mengenal kedua orang tuanya sudah ia lakukan: mencari tulisan-tulisan ayahnya di koran tempo dulu, menelusuri nama ibunya di daftar anggota beberapa organisasi non-pemerintah pada masa Orde Baru, hingga mengikuti aksi Kamisan secara rutin untuk mencari jejak mereka. Namun, tetap saja ia tidak mengenal siapa mereka sebenarnya. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mengisi kekosongan itu?
Beep! Beep! Suara klakson membuyarkan lamunannya.
“Kalo bawa motor jangan sambil melamun dong, Mas! Gila, lu hampir nabrak gue!” teriak seorang pengendara.
“Eh- iya- maaf, Bang,” jawab Galih yang masih tenggelam dalam pikirannya.
Saat itu, ia sebenarnya sedang dalam perjalanan menuju rumah Ii Iyen, bibi yang merawatnya sejak kecil. Sosok ibu satu-satunya yang ia miliki. Pagi tadi, Ii Iyen meneleponnya dan memintanya datang setelah pulang dari kampus negeri terbesar di Kota J, tempat Galih belajar ilmu kedokteran. Walau penampilannya sedikit berantakan karena polusi kota J, akhirnya ia tiba di rumah Ii Iyen. Dari luar, rumah itu tampak seperti rumah kosong. Gaya bangunannya yang kuno membuatnya terlihat agak seram. Namun, saat pintu dibuka, kehangatan memenuhi seluruh ruangannya. Nostalgia seolah menyelimuti Galih, membawa kembali kenangan-kenangan yang berenang di benaknya.
“Eh, si kasep tos datang,” sapa Ii Iyen dengan aksen Sunda yang sangat familier bagi Galih. Ii Iyen memang berdarah campuran Tionghoa dan Sunda, tetapi sangat fasih berbahasa Sunda karena pernah tinggal di Kota T.
“Halo, Ii Iyen. Ada apa, Ii? Kenapa tiba-tiba memanggilku?” tanya Galih.
“Selamat ulang tahun, Lih. Ii senang bisa terus bersamamu sampai sekarang, saat kamu sudah genap 21 tahun,” kata Ii Iyen sambil tersenyum, matanya berkaca-kaca.
“Kirain ada apa, Ii. Ternyata cuma mau ngucapin. Makasih banyak ya, Ii, sudah ngurus aku sejak kecil,” jawab Galih.
“Lih, tuang heula atuh. Ii sengaja masakin sayur asem jeung gurame goreng, favoritmu.”
Ii Iyen kemudian beranjak ke kamarnya, tetapi tak lama ia kembali dengan membawa sesuatu saat Galih sedang menikmati makanannya. Galih melirik ke arah benda itu dengan rasa penasaran.
“Kumaha, Lih? Hao chi?” tanya Ii Iyen.
“Iya, enak banget sayur asemnya. Gurame Nya juga,” jawab Galih sambil melanjutkan makannya.
“Itu apa, Ii? Buku, ya?” tanya Galih, menambahkan.
Ii Iyen mendekatkan benda itu, sebuah buku cokelat tua yang tebal dan terlihat kuno.
“Ini buat kamu, Lih. Ii sudah menyimpan buku ini sejak lama, dan memang rencananya akan Ii berikan di waktu yang tepat. Mungkin sekaranglah waktunya. Buku ini milik Raksa, ayahmu,” jawab Ii Iyen.
Suasana seketika menjadi hening. Galih sudah lama tidak mendengar nama ayahnya disebut, terutama sejak tragedi 1998.
“Simpan baik-baik, ya. Lihat semua isinya. Mungkin dari sini kamu akan mulai mengenal siapa ayahmu.”
Galih hanya terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca, dan kesedihan jelas tergambar di wajahnya. Ii Iyen memeluk Galih dengan hangat, seolah ingin menyalurkan seluruh kasih sayangnya. Dalam hati, Ii Iyen hanya berharap yang terbaik untuk Galih, berharap agar hidupnya dapat dirayakan sepenuhnya.