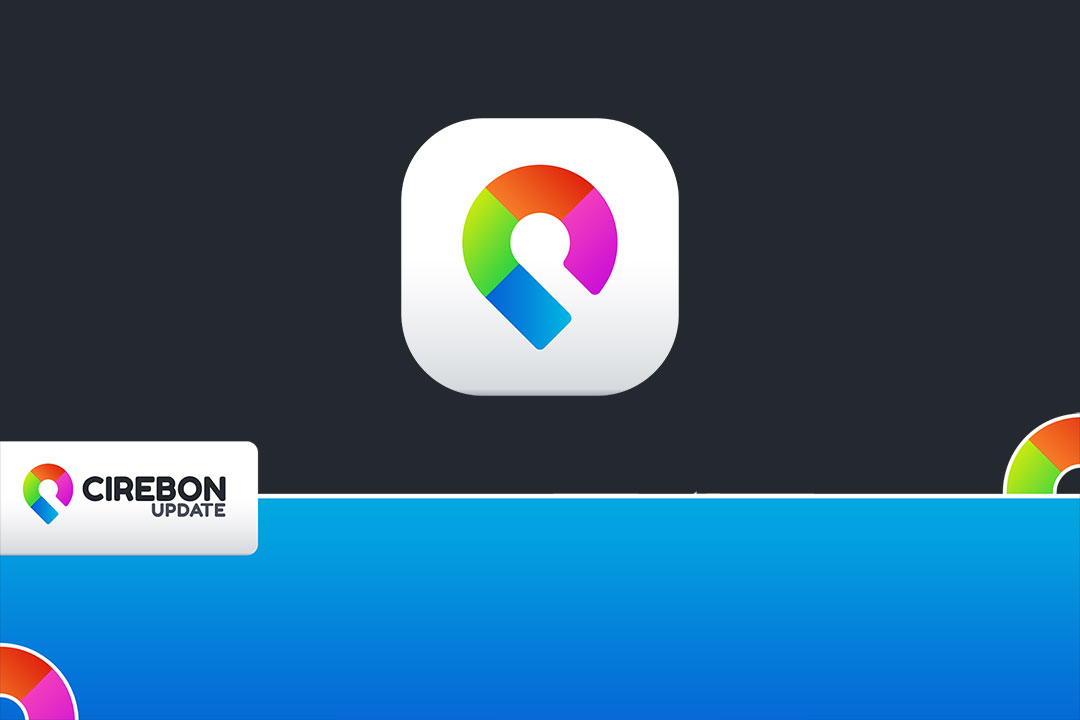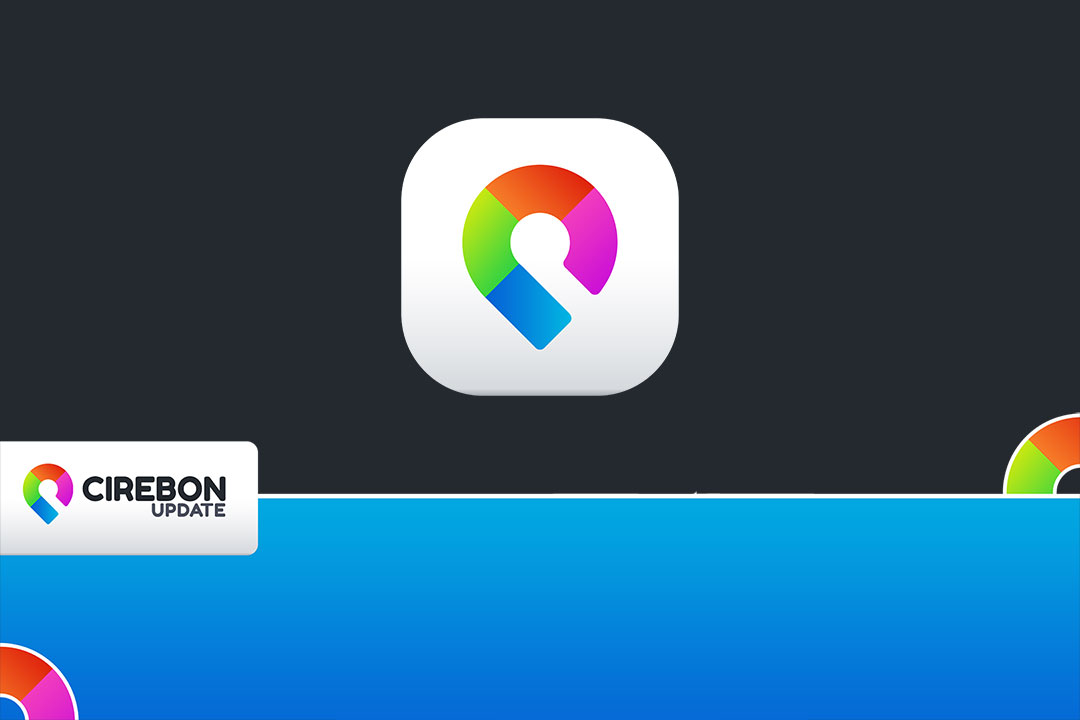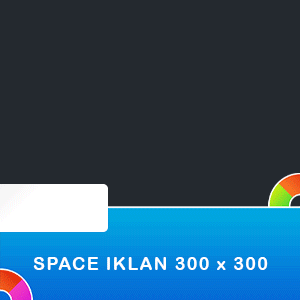Galih duduk terpaku. Surat itu terjatuh dari tangannya, melayang pelan sebelum akhirnya menyentuh lantai. Ia menatap kosong ke arah buku tua di pangkuannya. Napasnya pendek dan cepat, mencoba menenangkan badai emosi yang tiba-tiba datang seperti gelombang besar.
"Ayah..." gumamnya lirih. Perasaan asing merambati tubuhnya, semacam rasa kehilangan yang mendalam sekaligus pengertian yang baru.
Ia menutup buku itu perlahan, membiarkan pikirannya tenggelam dalam potongan-potongan cerita yang baru saja ia baca. Bayangan seorang pria yang mempertaruhkan segalanya untuk keluarganya, seorang wanita yang berani hingga akhir hayatnya dan seorang anak yang tak sadar tengah menjadi pusat cinta sekaligus korban kebencian dunia yang kejam.
Galih bangkit dari sofa, membawa buku itu ke meja kecil di sudut ruangan. Ia menyalakan lampu meja, cahaya hangat menerangi halaman-halaman yang usang itu. Jarinya menyentuh perlahan tulisan ayahnya, merasakan setiap guratan tinta yang memudar.
“Mimpiku dan kamu, Toko Batik Ramalan”
"Jadi, ini kenanganmu untukku, Ayah," bisiknya. "Ini yang kau tinggalkan, untuk memastikan aku tahu apa yang terjadi. Agar aku tak lupa."
Matanya tertuju pada puisi terakhir ayahnya, kata-katanya berulang kali terngiang di benaknya. "Tinggalkan Aku!" katanya. Apakah itu pesan untuk melupakan masa lalu? Atau justru sebaliknya untuk memahami dan belajar darinya, tanpa terjebak di sana?
Galih merasa, untuk pertama kalinya, ia mulai benar-benar memahami arti perjuangan kedua orang tuanya. Ia membuka kembali buku itu, menelusuri halaman-halaman berikutnya dengan hati-hati, berharap menemukan petunjuk lebih banyak tentang mereka apa yang mereka impikan, apa yang mereka perjuangkan, dan bagaimana ia bisa melanjutkannya.
Di halaman berikutnya, sebuah peta kecil terselip. Peta itu digambar dengan tangan, tinta biru yang sudah memudar menunjukkan jalan-jalan kecil dan tanda silang di sebuah lokasi. Di bawahnya tertulis singkat: "Kota T, di mana mimpi akan dimulai."
Galih termenung sejenak. Kota T, kota yang kecil yang hanya ia kenal sebagai asal-usul Ii Iyen. Mungkinkah ada sesuatu yang menunggu di sana? Atau ini hanya kenangan kosong yang ditinggalkan ayahnya?
Ia memasukkan peta itu ke dalam saku, berjanji pada dirinya sendiri untuk mencari tahu. Pikirannya kini dipenuhi dengan rencana-rencana: berbicara dengan Ii Iyen, menggali lebih dalam, dan mungkin, suatu hari nanti, membangun apa yang ia kenal sebagai toko batik bernama Ramalan. Tempat yang mungkin bisa mengisi semua kosongnya.
Namun, malam itu, ia hanya bisa memandang keluar jendela, menatap langit malam yang perlahan berubah menjadi fajar. Angin dingin menyelinap masuk dari celah-celah kecil di dinding, seakan membisikkan sesuatu yang menenangkan.
Di dalam hatinya, ia tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan untuk mengenal masa lalu, memeluk mimpi yang sempat terhenti dan menciptakan sesuatu yang baru dari serpihan-serpihan kenangan itu.
Saat fajar perlahan menyinari langit, Galih berdiri tegak, membawa buku tua itu dengan penuh kehormatan. Ia tahu, apapun yang terjadi ke depannya, ia tak lagi berjalan sendiri. Ia membawa cinta, keberanian, dan mimpi kedua orang tuanya bersamanya.
“Untuk Galih,
Semoga kamu selalu berpayung Tuhan yang baik, semoga segala sakit dan takutmu runtuh, semoga kamu selalu dirayakan, semoga raga kecilmu selalu dipeluk, semoga selalu mendambakan cinta, semoga semua baikmu terpupuk, semoga tanganmu selalu diwarnai oleh bahagia, semoga harum selalu namamu, semoga tenangmu hidup, semoga mimpi-mimpimu siap dibangun.
-Raksa, Ayahmu.
16 Mei 1998.”