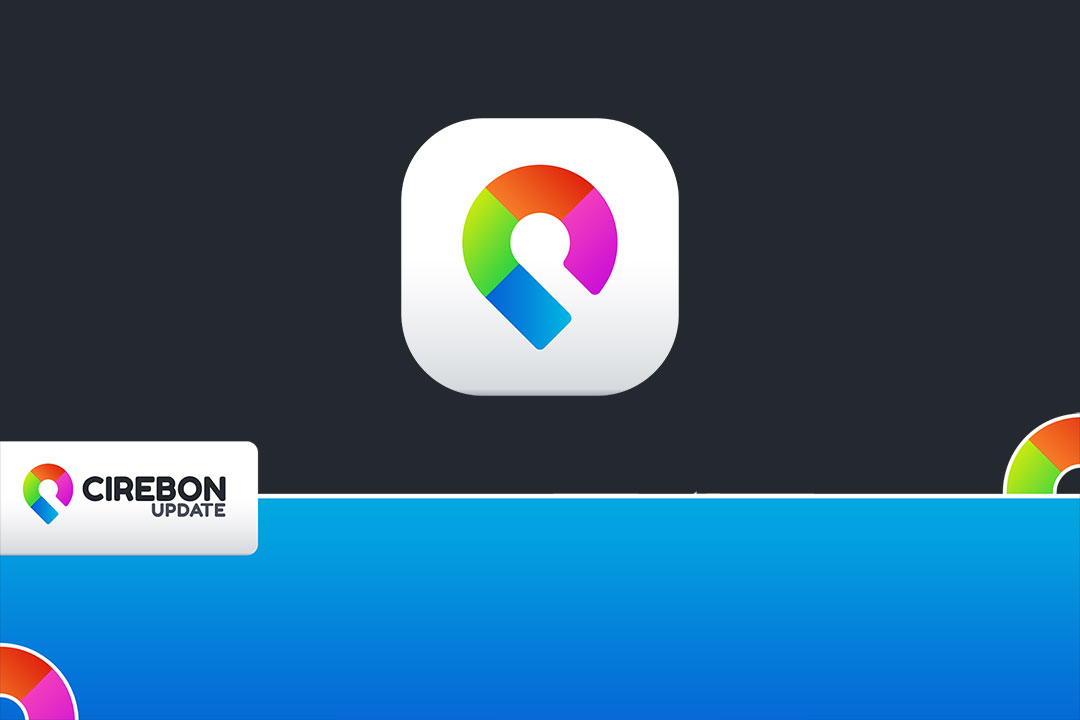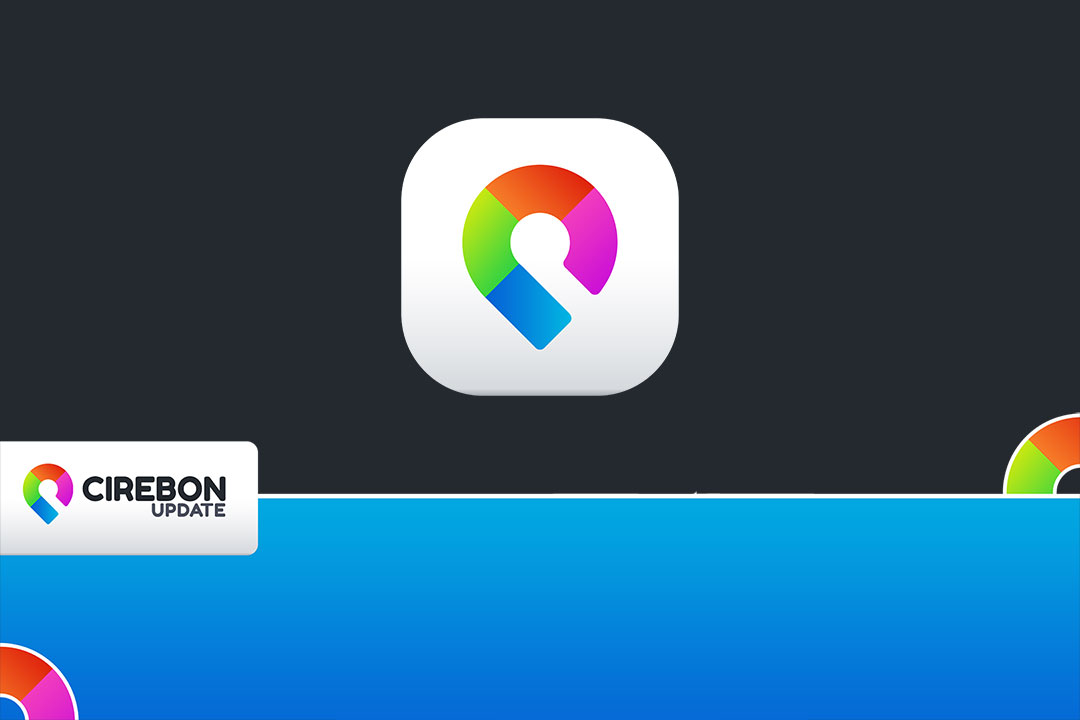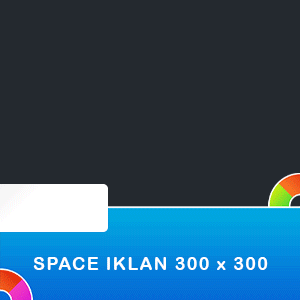Malam semakin larut. Langit gelap mulai bergeser, memberi ruang pada cahaya pertama fajar. Setelah makan, Galih mengambil buku tua milik ayahnya, buku yang menyimpan mimpi, cerita, dan puisi-puisi ayahnya.
Dia membuka halaman berikutnya, kali ini terpaku pada sebuah puisi yang ditulis dengan tinta hitam yang mulai memudar. Puisi itu terasa seperti pesan pribadi, seolah bukunya berbisik, memintanya untuk memahami lebih dalam mimpi yang diwariskan sang ayah.
Galih membaca perlahan, merenungi tiap kata:
“Tinggalkan Aku! Katanya.
Masa lampau patut dilampaui.
Ubahlah arahmu dan ketuklah pintu,
Karena sudahkah aku cukup memberi?
Pelangi setelah cerah juga pergi.
Tolong Tinggalkan Aku! Katanya.
Buka pintu yang sudah ada di depan mata!
Pelita akan menerangi dan membutakan.
Cahaya pun menyilaukan.
Rasa hangat panas api akan membakar kulitmu dan mengabu,
Tumbuhlah kamu dengan hama kedukaan,
Akhirnya terjebaklah akarmu itu.
Jadi tolonglah, tinggalkan Aku!”
-16 Mei 1998, Raksa”
“Raksa... bangun, boleh bantu aku dulu? Galih terbangun, aku masih harus menyelesaikan artikel lain. Maafkan aku.” Suara lembut Mala menyentuh telingaku, membangunkanku dari lamunan.
Matahari telah terbenam. Jarum jam menunjukkan pukul 19.00. Aku buru-buru naik ke kamar untuk menenangkan Galih yang menangis. Begitu melihat wajahku, tangisan bayi kecil itu seketika berhenti. Mungkin ia tahu, aku ada di sini untuk melindunginya. Dengan hati-hati, aku menggendong Galih ke teras rumah, menikmati udara malam dengannya.
Semenjak kelahirannya, dunia yang tadinya penuh kebencian berubah total. Galih mengajariku menjadi lebih lembut. Segala amarah yang dulu memenuhi hatiku perlahan luruh. Tiba-tiba, sebuah kecupan lembut menyentuh pipiku. Mala sudah selesai menulis.
“Mengapa aku yang lega melihat dia sudah tidak sibuk?” pikirku. Wangi khas yang aku suka tercium samar-samar, membuat hatiku hangat.
“Raksa, ini kopinya. Aku buat untukmu,” katanya sambil meletakkan segelas kopi hitam pekat di meja.
“Terima kasih ya, sayang,” jawabku dengan senyum kecil.
“Sini, biarkan aku yang gendong Galih,” ucap Mala, mengambil Galih dari pelukanku dengan lembut.
Kupikir dia akan masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata dia bersandar di bahuku sambil menggendong Galih. Momen seperti ini selalu membuatku merasa damai, bahkan di tengah ketakutan dan kerusuhan Kota J.