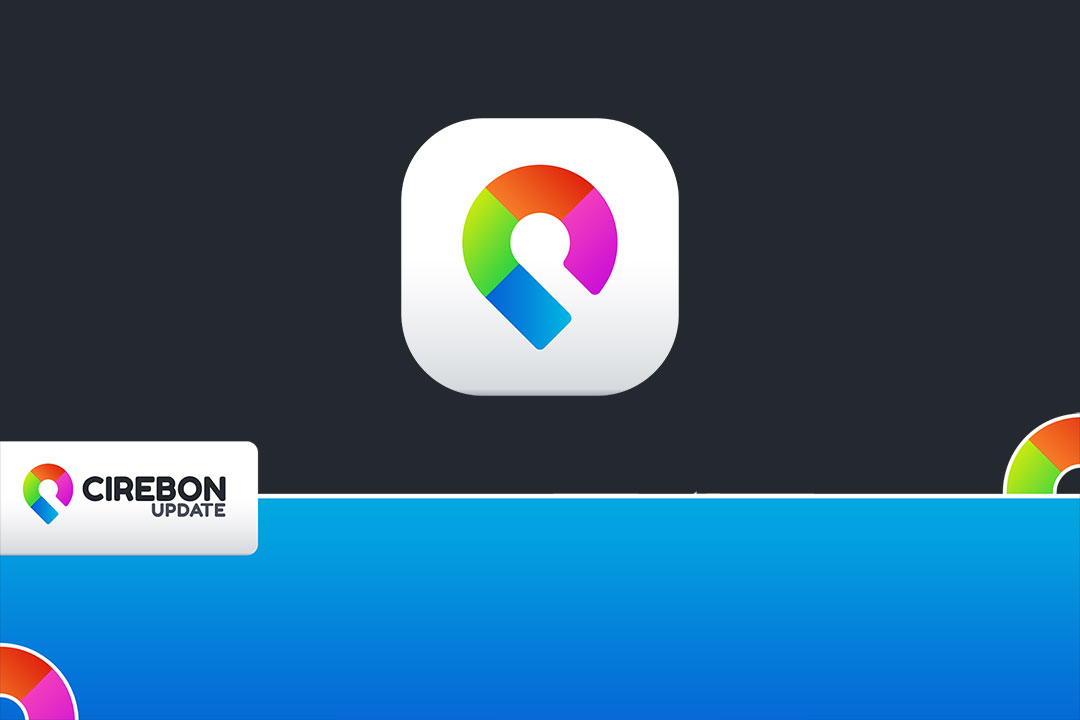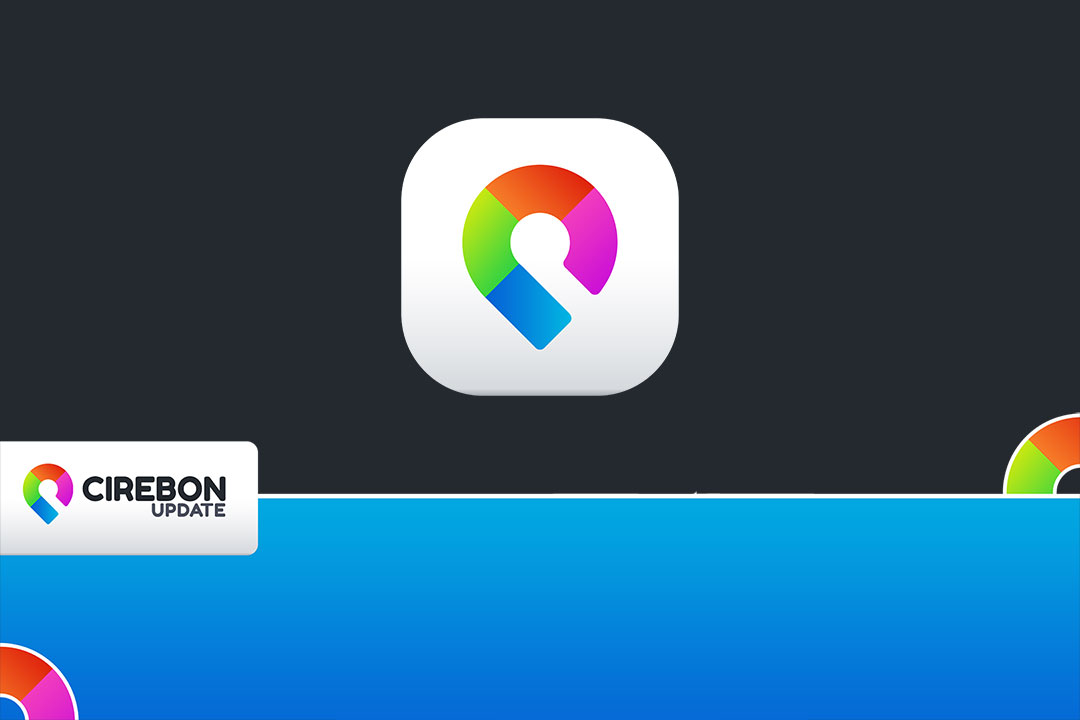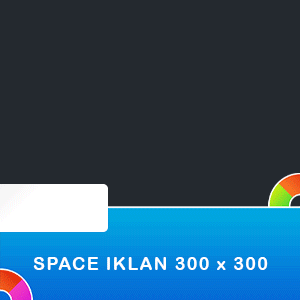Tak terasa, malam mulai menjelang. Langit yang gelap mengingatkan Galih untuk segera kembali ke rumah kontrakannya.
Malam itu, Galih hanya duduk termenung. Selama ini, ayahnya terasa seperti sosok yang hanya dapat disentuh melalui doa. Kini, nama itu kembali disebut, membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang lama terpendam. Apa kabar ayah sekarang? Apakah sudah bahagia di atas sana, atau masih terkurung dalam propaganda di jaman lawasnya? Bagaimana perasaan ayah? Di mana ayah sebenarnya?
Pikiran-pikiran itu terus menggelayut di benaknya sambil ia berbaring di sofa ruang tamu. Hingga tiba-tiba, ia teringat buku yang diberikan oleh Ii Iyen. Buku itu masih tersimpan rapi di dalam ranselnya. Rasa ingin tahunya memaksanya untuk segera membuka ransel tersebut.
Galih meraih buku itu. Sampulnya, yang terasa seperti terbuat dari kulit, sudah terlihat usang. Halaman-halamannya tampak menguning ditelan usia. Saat membuka bagian tengah buku, ia merasa ada sesuatu yang mengganjal. Ternyata, sebuah amplop usang terselip di sana. Di bagian depannya tertulis:
"Untuk kekasihku, Mala."
Galih membaca tulisan itu dengan saksama. "Mala? Ibu saya," gumamnya. Rasa ingin tahu yang semakin membuncah membuatnya langsung membuka amplop tersebut dan membaca isi suratnya.
“15 Mei 1998
Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat cela padamu. Sayangnya, aku tak bisa lagi melihatmu. Kematian telah menciummu dengan kecupan, sebagaimana engkau menciumku. Cintamu lebih nikmat daripada anggur, tetapi jiwamu telah terbakar dalam diriku dan akan selalu kuingat. Kematian begitu keji, membunuh kasihku. Sekarang, namamu selalu kusebut dalam doa, walau engkau telah bersama-Nya. Kusampaikan salam terakhirku perlahan-lahan melalui tulisan ini.
-Raksa”
Jakarta, 15 Mei 1998.
Pagi itu, komplek rumah kontrakkan saya dan istri terasa begitu sunyi. Mungkin karena orang-orang takut keluar rumah setelah tragedi dua hari lalu. Kematian telah menjemput empat teman saya oleh orang-orang yang berlindung di balik tameng kekuasaan. Perasaan saya bercampur aduk.
Di satu sisi, saya masih ingin melawan penguasa-penguasa gelap dunia ini. Di sisi lain, saya takut. Kami terpaksa menutup mulut atas segala ketidakadilan yang terjadi, seolah-olah ancaman selalu mengintai jika kita berbicara. Begitu pengecut para tikus-tikus berdasi yang gila materi, membungkam rakyat hanya karena takut akan realitas yang mereka hadapi.
Keluarga Mala juga banyak yang menjadi korban. Rumah mereka dibakar habis oleh massa yang dipenuhi sentimen terhadap etnis tertentu. Saya hanya memiliki satu ketakutan besar: keamanan keluarga kecil saya. Saya tidak mau Mala meninggalkan saya. Saya tidak mau Galih tumbuh tanpa seorang ayah.
Iyen, adik Mala, bersama beberapa anggota keluarga mereka yang masih selamat, memutuskan pindah ke Kota T untuk bersembunyi. Kemarin, ruko keluarga mereka habis dilahap api, meninggalkan trauma mendalam.
“Raksa, ayo sarapan dulu. Jangan terus-terusan menulis!” Suara Mala terdengar dari bawah tangga, sedikit berteriak.
“Iya, sayangku. Jangan terlalu sering berteriak, nanti suaramu habis. Siapa yang akan menyanyikan lagu buat dedek Galih?” Jawabku sambil turun menuju dapur.
Di meja makan, raut wajah Mala tampak lelah. Ia selalu sungkan meminta saya bergantian mengurus Galih, yang baru berumur tiga bulan. Katanya, ia tidak ingin mengganggu kesibukan saya menulis artikel untuk koran. Padahal, ia sendiri aktif di berbagai organisasi perempuan dan menjadi bagian dari anggota institusi pendidikan perempuan.
Bagiku, pekerjaannya begitu mulia. Mala selalu rendah hati dalam melayani rakyat dan tak pernah lelah memperjuangkan kesetaraan gender, sesuatu yang telah lama hilang dibungkam.
“Mala, kamu sarapan dulu saja. Biar aku yang mengurus Galih. Kamu istirahat ya, sayang,” ucapku lembut. Namun, seperti biasa, ia hanya tersenyum kecil dan tetap melanjutkan pekerjaannya.
Setelah selesai sarapan, saya mendapati Galih tertidur pulas dalam gendongan saya. Dengan hati-hati, saya membaringkannya di kamar agar tidurnya tidak terganggu. Lalu, saya beranjak merapikan rumah. Menurut saya, pekerjaan rumah bukan hanya tugas istri, melainkan tanggung jawab bersama.