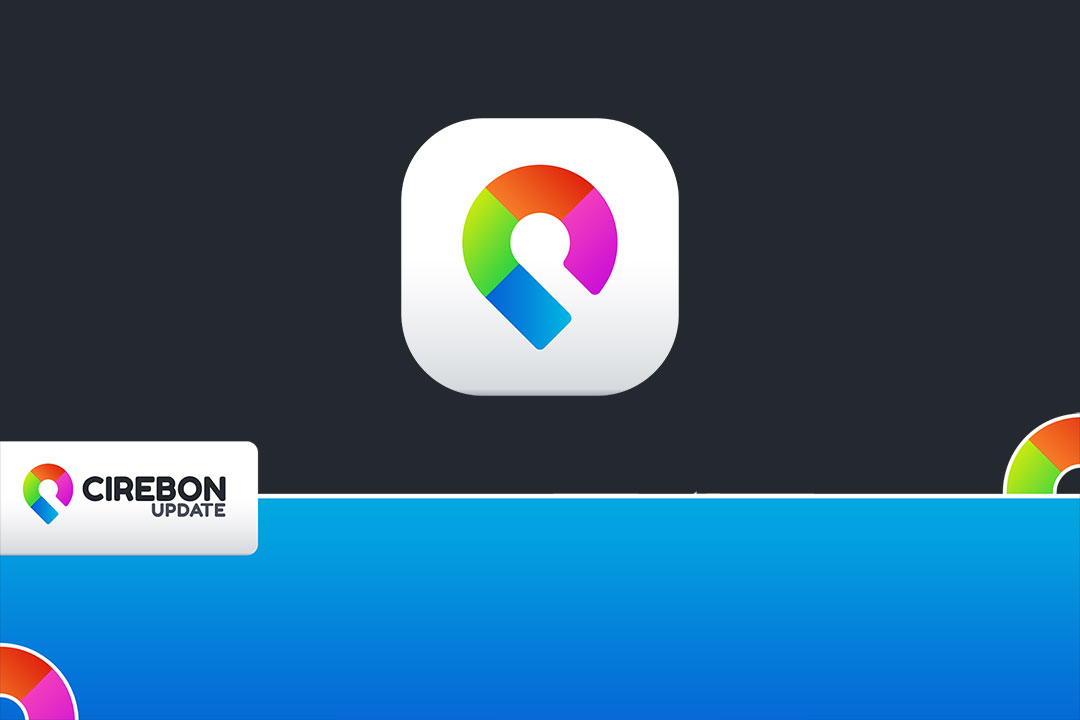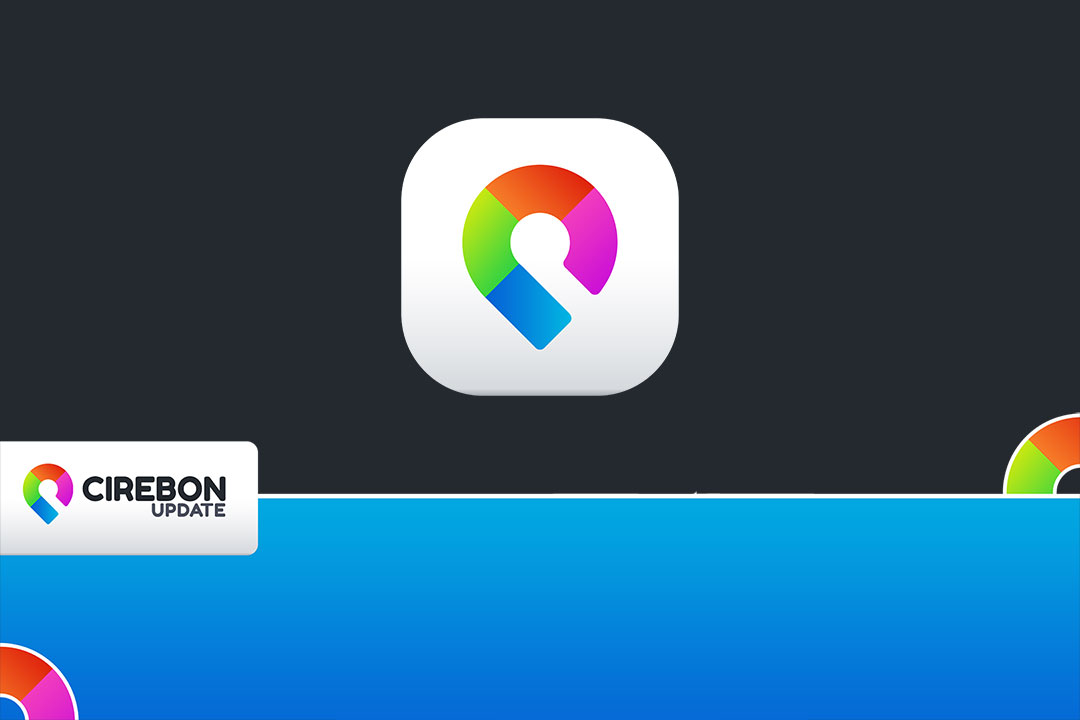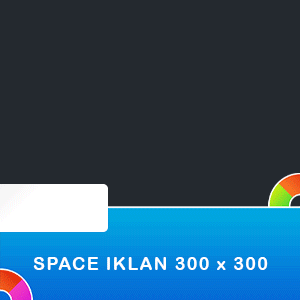Namun, ketenangan kami seketika pecah. Suara gaduh dari kejauhan mulai terdengar, samar-samar, tetapi makin lama semakin mendekat. Riuhnya membangkitkan firasat buruk.
“Mala, bawa Galih masuk dan bersembunyilah!” kataku tegas.
Dari teras, aku melihat kerumunan orang-orang yang membawa senjata seadanya terlihat di tangan mereka. Amarah tampak membara di wajah-wajah itu.
“Ada apa ini?!” tanyaku dengan suara lantang.
“Mana Mala?! Suruh keluar sekarang!” teriak salah satu dari mereka.
“Maksud kalian apa?” aku balik bertanya, mencoba menahan emosi.
“Tahukah kau semua kericuhan ini terjadi karena orang-orang seperti dia! Aktivismenya mengganggu.” jawab mereka yang menganggap aktivisme sebagai bentuk protes yang radikal. Apakah mereka sebenarnya tahu bahwa kita semua satu tujuan, ingin memajukan negeri ini dan menghilangkan sistem otoriter?
“Salah apa istri saya?! Para aktivis juga bagian dari negeri ini! Lagian, istri saya tidak ada di rumah. Dia sudah pergi, entah ke mana!” balasku dengan suara bergetar.
“Tahu apa kau tentang keadilan?! Kau juga sama saja ya?” suara mereka semakin lantang, menyeret nama istri dan keluarganya.
“Ayo, kita grebek saja rumahnya!” cetus salah satu dari mereka, disambut sorakan setuju.
Firasatku semakin buruk. Aku bergegas masuk ke dalam rumah, menggendong Galih yang mulai menangis. Warga-warga itu mulai mendobrak pintu, menghancurkan barang-barang di dalam rumah. Aku menyuruh Mala untuk segera mengemasi beberapa barang dan bersiap kabur.
Tangisan Galih semakin keras, tapi aku memeluknya erat, berusaha menenangkannya. Kerumunan itu terus berteriak, memaksa kami keluar untuk "diadili."
Akhirnya, aku, Mala, dan Galih terpaksa turun. Mala tampak pucat, ketakutan. Ia menggenggam tanganku erat-erat, matanya berkaca-kaca, menahan tangis.
“Cepat turun! Jangan lambat-lambat!” teriak salah satu dari mereka dengan penuh kebencian.
Aku membisikkan sesuatu ke Mala. “Bawa Galih, kaburlah. Aku akan menghadapi mereka.”
Mala ragu, tapi akhirnya menurut. Ia lari keluar pintu. Namun, dalam kepanikannya, ia meninggalkan Galih dalam gendonganku. Tangisan Galih tak menghentikan kemarahan mereka. Seakan, kemanusiaan mereka telah lama mati.
Mala terus berlari. Sampai... DOR! DOR! DOR!
Tiga peluru menembus punggungnya. Tubuhnya jatuh ke tanah. Waktu seolah berhenti.
“MALA!” teriakku, gemetar. “Biarkan aku saja yang kalian bunuh! Jangan Mala!” Aku masih berharap dia bisa bertahan.
Dengan sisa tenaganya, Mala menoleh ke arahku. “Bawa Galih pergi, Raksa…” bisiknya pelan, sebelum tubuhnya tak lagi bergerak.
Aku tahu aku harus segera pergi. Tembakan lain mulai dilepaskan, mengejarku yang menggendong Galih. Sambil membawa tas ransel dengan beberapa barang, aku berlari tanpa tujuan, hanya ingin menyelamatkan anakku.
Aku akhirnya menghubungi Iyen, adik Mala. Dia memberi alamat sebuah gubuk kecil di tempat tersembunyi. Aku tiba di sana dalam keadaan kacau, masih sulit percaya Mala telah tiada. Gubuk itu sempit, hanya cukup untuk satu orang, tetapi aman untuk sementara waktu.
Malam itu, setelah Galih akhirnya tertidur, aku duduk dalam gelap, menulis surat terakhir untuk istri yang kucintai.
"Untuk Kekasihku, Mala"